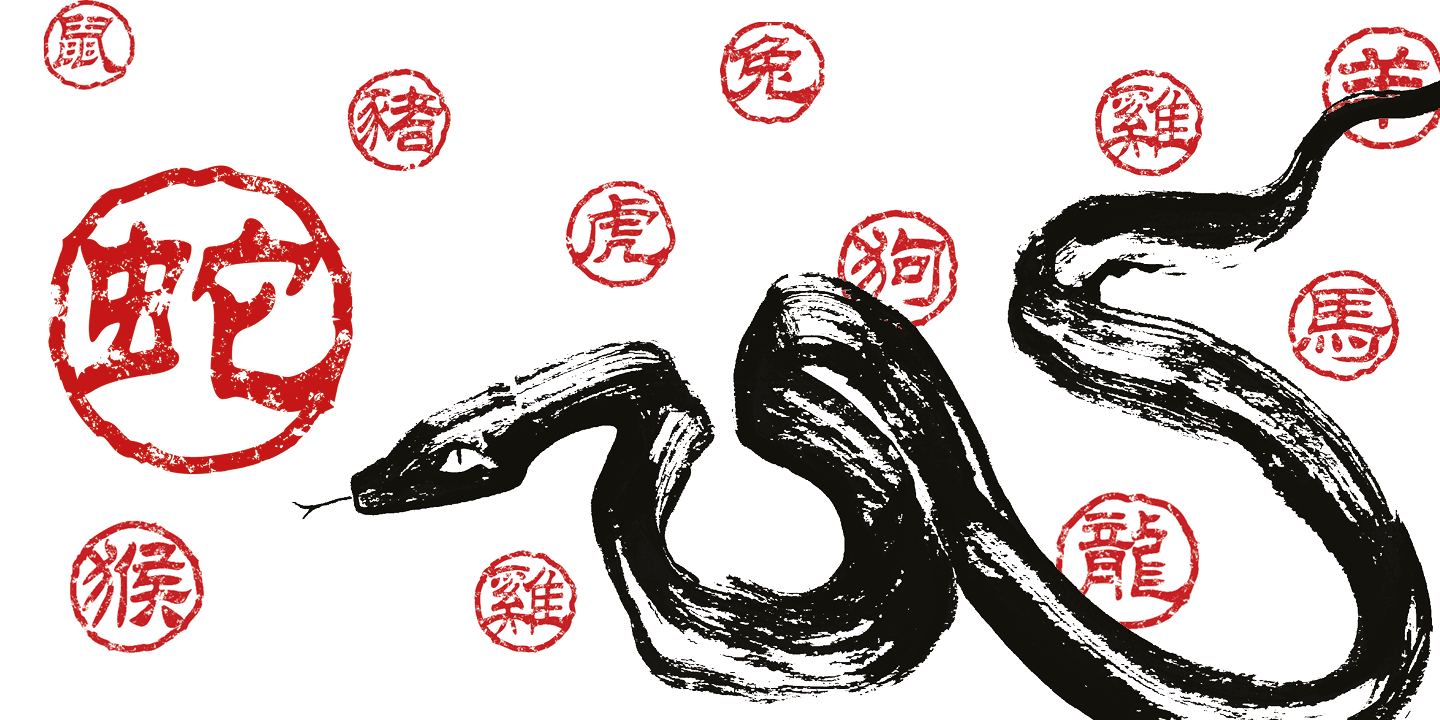28 September 2022
Andini Effendi: Harga Dari Sebuah Kemerdekaan

Ariish Wol (MiLK Model Management) photography by Meinke Klein for ELLE Indonesia September 2022
Saat menulis artikel ini, ibu saya sudah 5 minggu terbaring dalam perawatan di rumah sakit. Beliau divonis kanker pankreas stadium lanjut pada hari Natal 2021 silam. The journey onwards has been a ride to say the least. Ibu percaya ketika saya diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup, saya pasti akan memberikan lebih dari yang beliau harapkan. Sejak remaja, saya sudah bercita-cita menjadi wartawan. Bapak sempat mempertanyakan pilihan saya ini. Tetapi tidak dengan ibu. Ibu selalu membebaskan saya untuk memilih jalan hidup.
Dulu ketika saya pergi liputan selama 3 bulan meliput konflik di Libya, ibu hanya satu kali mengirim pesan Blackberry dan menanyakan nomor telpon seseorang. Saya sampai berpikir, “Sudah gila rupanya ibu gue. Masa anaknya sedang di medan perang, dia malah mengirim pesan BBM hanya untuk bertanya nomor telpon orang lain?”. Kalau dibandingkan bapak yang sangat sering menelpon untuk memastikan saya masih hidup, ibu justru sangat cuek. Bertahun-tahun kemudian saya bertanya pada ibu, kenapa kok dia tidak mengecek saya terus-menerus seperti bapak? Jawabnya singkat, “Nanti malah mengganggu kamu kerja.”
Dulu saya pernah bertanya pada orangtua, “Apakah boleh saya menikah dengan laki-laki berbeda agama?” Sontak Bapak langsung mencetus, “Enggak boleh dong! Harus seagama!” Sementara ibu hanya tersenyum. Beberapa tahun kemudian pada suatu kesempatan ibu menyeletuk, “Kamu ingat tidak pembicaraan sama bapak soal kawin beda agama? Ibu juga sebenarnya mempertanyakan waktu itu memang kenapa sih nikah beda agama itu mesti dipermasalahkan. Heran ibu.” Pernyataan beliau inilah yang akhirnya membuat saya berani mengenalkan kekasih saya kepada ibu, bahkan salah satunya seorang Yahudi Israel. Dan ibulah yang melakukan ‘sweet talk’ kepada bapak mengenai pacar saya ini. Sampai bapak pun akhirnya kalem ketika kali pertama bertemu.

Clarita (Balitar) & Yen (WYNN) photography by Yohan Liliyani for ELLE Indonesia February 2019 styling Sidky Muhamadsyah
Sejujurnya, hubungan saya dengan ibu bukanlah seperti sepasang sahabat. Malah seringkali kami berbeda pendapat. Ada satu kejadian ketika saya remaja yang akhirnya membuat saya sempat tidak berbicara dengan ibu selama setahun lebih. Bisa dibilang ini bagian dari rebellious phase yang pernah saya alami. Dan karena kami berdua sama-sama keras kepala, maka jadilah kami bisa tidak bertegur sapa selama sekian lamanya.
Tahun 2020, saya sakit hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur, tapi hanya bilang ke ibu kalau saya sedang tidak enak badan. Ibu jarang sekali berkunjung ke apartemen saya. Tapi tiba-tiba suatu hari ibu datang membawa makanan. Melihat saya terkulai lemas, beliau langsung membawa saya ke rumah sakit. Untungnya tidak ada yang serius. Karena saya bersikeras tidak mau menginap di rumah orangtua, maka ibu hampir setiap hari mengirim makanan. Hal ini juga ibu lakukan ketika saya terpapar Covid-19. Tidak ada hari tanpa masakan rumah kirimannya.
Suatu hari di bulan Desember 2021, ibu mengirim pesan WhatsApp. Katanya badan ibu tidak enak. Waktu itu saya sedang sangat sibuk bekerja. Akhir pekan yang biasanya saya sempatkan mengunjungi ibu pun sering kali terlewat. Beliau sama sekali tidak pernah mengeluh kalau saya sedang sibuk bekerja sampai-sampai tidak meladeni dia. Sepertinya beliau senang melihat saya aktif bekerja, and make it on my own. She lived her idea of independence through me. She wanted to do the things that I am capable of doing. Sebab saya bisa melakukan apa yang mungkin dulu dia ingin lakukan tapi tak memungkinkan karena ibu menikah di usia 25 tahun kemudian memiliki anak.

Clarita (Balitar) & Yen (WYNN) photography by Yohan Liliyani for ELLE Indonesia February 2019 styling Sidky Muhamadsyah
Saat saya menyelesaikan bagian akhir tulisan ini, ibu saya baru saja berpulang. Ibu pergi dengan damai saat saya ada di sampingnya. Ibu mengembuskan napas terakhir usai kami berdua berbincang berbagi mimpi bersama yang kelak ingin kami berdua wujudkan kalau dia sudah sembuh.
Saya masih dalam fase tidak bisa berada dalam suatu tempat seorang diri. Bahkan saya belum berani pulang ke apartemen tanpa ada yang menemani. Rasa sepi masih menakutkan untuk saya. Cukup miris bagi seseorang yang selama ini selalu merdeka melakukan apa pun sendiri.
Apakah saya menyesal karena kebebasan saya akhirnya malah menyisakan sedikit waktu bagi ibu? Apakah saya kecewa bahwa ibu tidak bisa melihat lagi apa yang bisa saya raih dalam hidup dengan kemerdekaan saya sebagai perempuan? Apakah saya frustrasi dengan kebebasan saya yang kali ini harus terukur karena prioritas pun berubah? Jawabannya tidak. Apa yang terjadi di masa lalu membentuk apa yang harus saya lakukan di masa depan.
Our freedom evolved as our priority changed. And that’s the price of my independence. For that, I am forever grateful.